Banyak kenangan yang kudapat di
sini. Kenangan bersama Ria, Alika, dan..
Robi... Salah satunya di bawah
pohon cemara ini. Entah mengapa, bagiku pohon cemara itu memberiku obsesi besar
akan indahnya persahabatan. Dan, bunga krisan yang kami tanam sepuluh tahun lalu
di pohon cemara ini, telah banyak berbunga. Wanginya yang khas banyak
menebarkan aroma kesejukan di sekitar padang ilalang yang menutupi sekeliling
cemara ini.
Ah, indahnya kala itu…
Aku mengusap pelan batang cemara
yang masih berukir namaku dan sahabatku. Ukirannya masih tampak jelas meski
hampir pudar dimakan waktu. Pikiranku bernostalgia ke masa itu. Saat-saat itu..
masa-masa indah itu..
Aku memperhatikan cemara itu.
Batangnya masih kokoh dan daunnya masih tampak hijau dan segar. Bahkan, pohonnya
makin tinggi dan bercabang. Aku ingat, saat itu aku mencoba memanjatnya untuk
mengambil ‘kok’ yang tersangkut di ujung dahannya. Tapi tak mampu, dan Robi
yang berkursi roda saat itu membantu dengan menjulurkan bambu yang kebetulan
tergeletak di ujung kursi rodanya.

Aku duduk di hamparan rumput di bawah naungan sejuknya pohon cemara. Angin sepoi-sepoi meniupkan aroma khas daun krisan. Mataku terpejam, kembali memilah memori indah di sini. Ah, aku duduk memeluk lutut. Menikmati matahari sore, dan angin bertiup pelan, meniup poniku.
Aku duduk di hamparan rumput di bawah naungan sejuknya pohon cemara. Angin sepoi-sepoi meniupkan aroma khas daun krisan. Mataku terpejam, kembali memilah memori indah di sini. Ah, aku duduk memeluk lutut. Menikmati matahari sore, dan angin bertiup pelan, meniup poniku.
Aku melihat arlojiku. Hm, sebentar
lagi dia akan muncul.
“Fariska?”
Ng? Aku menoleh. Mataku menyipit.
Lalu, aku tersadar. Dia tiba…
“Apa kabar? Sudah lama aku tidak
kemari,” dia duduk di sebelahku.
Dia memetik setangkai krisan. “Hm,
bunga krisan ini tumbuh subur. Tak sia-sia kita menanam dulu.”
“Ya,” aku tersenyum. Dia tak banyak
berubah dari sepuluh tahun yang lalu. Kamera kesayangannya masih saja
disampirkan di lehernya, seperti waktu itu.
“Bagaimana dengan karirmu,
Fariska?”
“Begitulah, terkadang membosankan
tiap hari harus berkutat dengan klien dan komputer,” aku memeluk kakiku.
“Bagaimana denganmu, Ria?”
Ria tersenyum. “Menyenangkan. Aku
bersyukur telah memilih menjadi fotografer.”
“Baguslah.”
Lalu kami diam. Mungkin Ria ingin
menikmati saat ini, mengenang saat itu.
“Bagaimana dengan Alika? Robi?”
tanyaku pelan.
Terdengar helaan nafas berat. Aku
menoleh padanya, meminta jawaban.
“Begitulah, Ka,” suara Ria serak.
“Alika pindah ke New Zealand, mengikuti ibunya. Sejak orang tuanya bercerai,
dia menjadi pemurung. Ibunya memenangkan atas hak asuh dan dia mengikuti ibunya
ke New Zealand, tempat ayah barunya. Ya, ibunya menikah dengan warga negara
sana.”
Aku terpukul mendengarnya.
“Kau masih sering menghubunginya?”
tanyaku.
Ria menggeleng. “Dia pindah delapan
tahun yang lalu, tanpa pamitan dan tanpa tinggalkan email dan nomor yang bisa
dihubungi.”
Aku membisu. Alika…
“Robi?”
Setetes air mata mengambang di
sudut matanya. Pelan, tangannya mengusap. Aku menggenggam erat rumput di
sekelilingku. Aku takut akan jawabannya.
“Robi meninggal lima tahun yang
lalu. Kankernya sudah tak mungkin disembuhkan. Sebuah keajaibanlah yang
membuatnya bertahan hingga saat itu. Kau tahu, Fariska? Dia menyimpan penyakit
itu dengan susah payah. Dia ingin, kita tetap bersama sela…”
Perkataan Ria terputus oleh tangis.
Aku menyeka mataku yang berair.
“Robi meninggal delapan agustus.
Dia dimakamkan di Gorontalo, tempat kelahirannya,” tukas Ria, diiringi isak
pelan.
Pikiranku melayang, menjelajah.
Duh, aku tak tahu apa-apa tentang sahabatku semenjak aku memutuskan untuk
bersekolah di luar negeri. Aku menyesal telah meninggalkan mereka. Aku… aku…
Tiba-tiba, ponsel Ria berbunyi.
“Halo? Apa? Oh, ya, baik. Kapan?
Sekarang? Ya, ya. Oke.”
“Fariska,” Ria menyentuh pelan pundakku.
“Ya?”
“Aku harus pergi,” dia bangkit dari
duduknya.
Aku berdiri dan mengangguk pelan.
“Hati-hati,” pesanku sambil
merangkulnya.
Ria tersenyum tipis dan berlalu.
*****
Setengah jam yang berarti
Aku memeluk lutut dalam diam. Pikiranku
menerawang. Masih ada rasa penyesalan dalam hati. Aku menyesalkan tindakanku
sepuluh tahun yang lalu. Keputusanku untuk belajar ilmu fisika dan mendalaminya
di negeri matahari terbit, suatu langkah yang salah. Karena keputusanku itulah,
aku harus kehilangan dua sahabatku.
Aku menatap pelan matahari yang
hampir tenggelam. Cahayanya memberikan bayangan di pangkal pohon cemara. Pohon
cemara bergemerisik pelan, ditiup angin. Aku merapatkan jaketku.
Hm, aku berdiri. Hampir malam.
Sebelum pergi, aku kembali mengusap ukiran namaku di batang kokohnya. Untuk
terakhir kali. Ya, aku harus kembali ke Jepang, untuk selesaikan masa kontrak.
Dan, entah kapan aku harus kembali lagi ke sini.
Matahari telah tenggelam
sepenuhnya. Aku meninggalkan pohom cemara itu. Bunyi gesekan langkah kaki dengan
rumput, gesekan daun pohon cemara, suara binatang malam, dan aroma bunga krisan
memenuhi sekelilingku.
Indah, serenade simfoni terindah
dalam hidupku…
*****





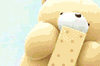
0 komentar:
Posting Komentar